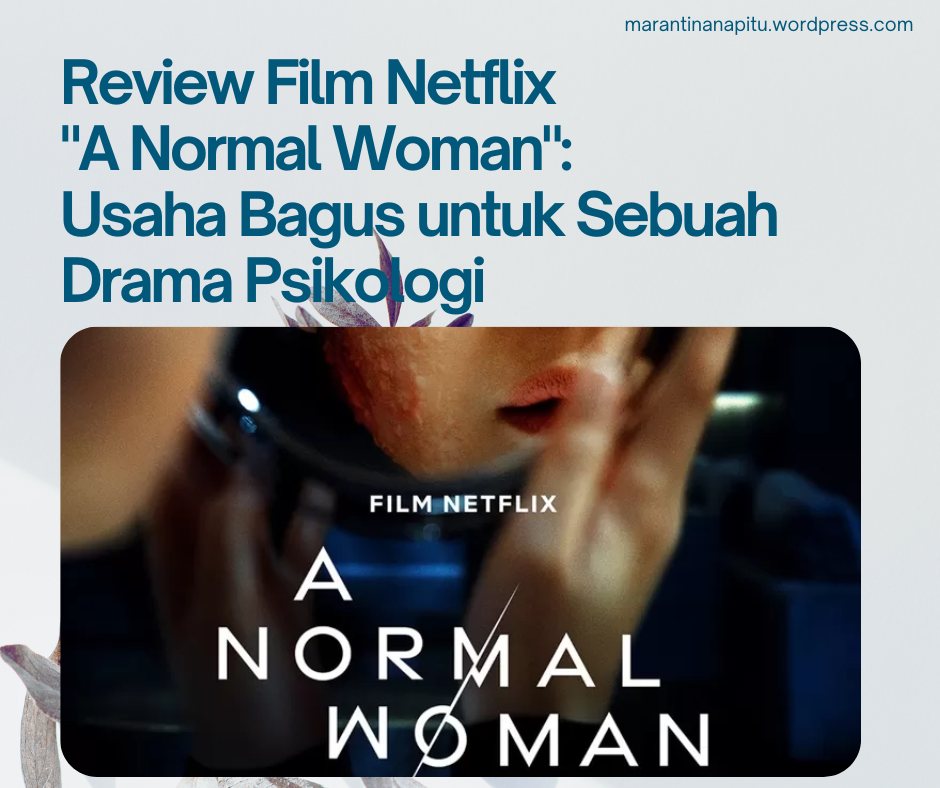## Ulasan Film “A Normal Woman”: Drama Psikologi Indonesia yang Menjanjikan, Namun Belum Sempurna
Film drama psikologi kerap memberikan pengalaman menonton yang berkesan, meninggalkan jejak mendalam di benak penonton. Ada film-film seperti “Fight Club,” “Interstellar,” “Gone Girl,” “Se7en,” dan “Parasite” yang menjadi contoh sempurna bagaimana genre ini mampu menciptakan karya sinematik yang tak terlupakan. Namun, tidak semua film drama psikologi berhasil mencapai standar tersebut. Seringkali, karya yang kurang matang justru meninggalkan rasa kecewa. Lalu bagaimana dengan “A Normal Woman,” film Netflix terbaru yang dibintangi Marissa Anita?
Sejak trailernya dirilis sebulan lalu, saya sudah sangat antusias menantikan penayangan film ini. Nama Marissa Anita sebagai pemeran utama menjadi daya tarik tersendiri. Begitu film ini tersedia di Netflix, saya langsung menontonnya. Berikut ulasan lengkapnya:
**Mengenal Karakter Utama dan Pendukung “A Normal Woman”**
Marissa Anita berperan sebagai Milla, istri Jonathan (Dion Wiyoko), seorang CEO perusahaan wellness yang tampak sebagai pasangan ideal: kaya, sukses, dan harmonis. Namun, di balik gemerlap kemewahan, tersimpan ketidakharmonisan. Jonathan berada di bawah bayang-bayang ibunya, Liliana (diperankan dengan apik oleh Widyawati), yang dianggap sebagai pusat kehidupan dan kunci kesuksesannya.
Kehidupan Milla yang serba berkecukupan ternyata menyimpan permasalahan. Ia harus menghadapi beban finansial dari ibunya yang bergantung padanya, dan anaknya, Angel, yang kerap menjadi korban bullying karena penampilannya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang sempit (kulit putih, mulus, kurus, cantik – standar yang, jujur saja, sangat tidak realistis).
Karakter pendukung lain yang penting adalah Bi Irah (Sari Koeswoyo) dan Erika (Giselle Anastasia), yang memainkan peran krusial di pertengahan hingga akhir film. Aida Nurmala juga turut serta sebagai sosialita kaya yang jujur dan blak-blakan, peran yang cukup familiar bagi penonton Indonesia.
**Plot yang Menarik, Namun Terganjal oleh Beberapa Kelemahan**
Adegan-adegan awal “A Normal Woman” memang menjanjikan. Kita disuguhkan gambaran kehidupan Milla dan Jonathan di rumah mewah, namun semua itu ternyata hanya sebuah pencitraan untuk citra merek “Eternal Life”. Kita langsung merasakan kegelisahan Milla, baik dalam kehidupan nyata maupun batinnya.
Milla diperlakukan sebagai perempuan kedua di rumahnya sendiri, harus tunduk dan memenuhi keinginan mertuanya. Di sisi lain, ia juga harus menghadapi tekanan dari ibunya yang seakan-akan Milla memiliki hutang budi padanya. Satu-satunya yang mendukungnya adalah Angel, putrinya. Penampilan Milla yang dianggap kurang menarik dibandingkan anggota keluarga lainnya juga menjadi sumber cemoohan.
Tekanan ini berdampak besar pada psikologis Milla, hingga ia dihantui sosok Grace, seorang anak kecil berlumuran darah. Mimpi buruk ini, ditambah ruam yang muncul di leher dan menyebar ke wajahnya, semakin memperparah kondisi Milla. Identitas Grace dan kaitannya dengan permasalahan Milla menjadi misteri yang baru terungkap setelah kemunculan Erika, teman lama Milla.
Puncak konflik terjadi pada perayaan ulang tahun Liliana. Milla yang awalnya ditunjuk sebagai event organizer, harus menghadapi berbagai konflik keluarga yang membuat pesta tersebut berjalan tidak sesuai rencana.
**Review: Potensi Besar, Namun Belum Termaksimalkan**
Awal film “A Normal Woman” memang sangat menjanjikan dan berhasil membangkitkan rasa penasaran. Pengenalan karakter yang terstruktur dan efektif membuat kita langsung terhubung dengan mereka. Sayangnya, di pertengahan hingga akhir film, terdapat beberapa elemen klise dan adegan drama yang terasa berlebihan dan justru mengurangi kualitas film.
Sebagai drama psikologi, saya merasa relate dengan tekanan sosial yang dihadapi Milla. Namun, saya sedikit kecewa karena Milla tampak pasif dan kurang mampu memperjuangkan dirinya sendiri. Dengan segala privilese yang dimilikinya, sutradara Lucky Kuswandi dan penulis skenario, menurut saya, belum berhasil memberikan kekuatan dan agency yang cukup pada karakter Milla.
Meskipun demikian, saya menghargai usaha dalam penggambaran karakter yang tidak hitam putih. Jonathan dan Liliana, meskipun tampak mengontrol kehidupan Milla, ditampilkan dengan nuansa yang lebih kompleks, bukan sekadar villain dangkal. Mereka memiliki niat baik, namun tindakan mereka telah menciptakan trauma mendalam bagi Milla dan Angel.
Akting Marissa Anita cukup baik, namun saya merasa ia masih bisa berakting lebih maksimal. Saya masih melihat Marissa Anita, bukan benar-benar sosok Milla, perempuan kaya, cantik, pintar, dan sophisticated.
Kekecewaan terbesar saya terletak pada akhir film yang terasa bertele-tele dan kurang klimaks. Misteri sosok Grace, yang menjadi kunci permasalahan Milla, tidak diungkap dengan cara yang cukup dramatis.
Kesimpulannya, “A Normal Woman” merupakan sebuah usaha yang patut dihargai dari sineas Indonesia dalam menghadirkan drama psikologi. Namun, untuk standar Netflix, saya berharap lebih. Semoga di masa mendatang, Netflix dapat menghadirkan drama psikologi Indonesia yang lebih matang dan berbobot.